Untuk pertama kalinya naskah tersebut diteliti oleh K.F. Holle, kemudian diteruskan oleh C.M. Pleyte. Kemudian naskah ini dialihbahasakan oleh Purbacaraka, sebagai tambahan terhadap laporan mengenai Batu Tulis di Bogor. Upaya tersebut diteruskan oleh H. ten Dam (tahun 1957) dan J. Noorduyn (laporan penelitiannya dalam tahun 1962 dan 1965). Selanjutnya naskah ini juga diteliti oleh beberapa sarjana Sunda, di antaranya Ma’mun Atmamiharja, Amir Sutaarga, Aca, Ayatrohaédi, serta Édi S. Ékajati dan Undang A. Darsa. Naskah Carita Parahiyangan berisi kisah para penguasa kerajaan Sunda yang berkedudukan di keraton Sri “Bima Punta Narayana Madura Suradipati” di ibukota Pakuan Pajajaran. Ada beberapa hal menarik yang tergambarkan dalam sistem pemerintahan kerajaan Sunda tersebut. Pertama, sistem pembagian kekuasaan didasarkan atas Tri Tangtu di Buana yang terdiri atas golongan: Prebu yang bisa ditafsirkan sebagai pemegang lembaga éksekutif, Rama yang bisa ditafsirkan sebagai pemegang lembaga législatif, dan Resi yang bisa ditafsirkan sebaga pemegang lembaga yudikatif; Kedua, sistem birokrasi kerajaan didasarkan atas sistem déséntralisasi yang terbagi menjadi 12 penguasa wilayah; dan Ketiga, modél pengaturan pemerintahan yang dikelola melalui pangwereg yang bersifat top down dan pamwatan yang bersifat bottom up dalam upaya meningkatkan stabilitas otonomi daérah demi kesejahteraan masyarakat. Naskah Carita Parahiyangan banyak menyebut nama tempat/wilayah yang termasuk dalam kekuasaan Sunda dan juga tempat-tempat lain di pulau Jawa dan pulau Sumatera. Sebagian dari nama-nama tempat tersebut masih ada sampai sekarang.
Isi naskah tersebut telah mampu memberikan sebagian gambaran bahwa masyarakat Sunda di masa lampau telah memiliki satu taraf kehidupan sosial kemasyarkatan yang cukup teratur, seperti juga sebagian masyarakat lainnya yang ada di Nusantara. Masyarakat lama telah mewariskan sesuatu yang mungkin sama sekali di luar perhitungan dan perkiraan kita saat ini. Makin Tahu Indonesia yah.
 INIMAHSUMEDANG
INIMAHSUMEDANG
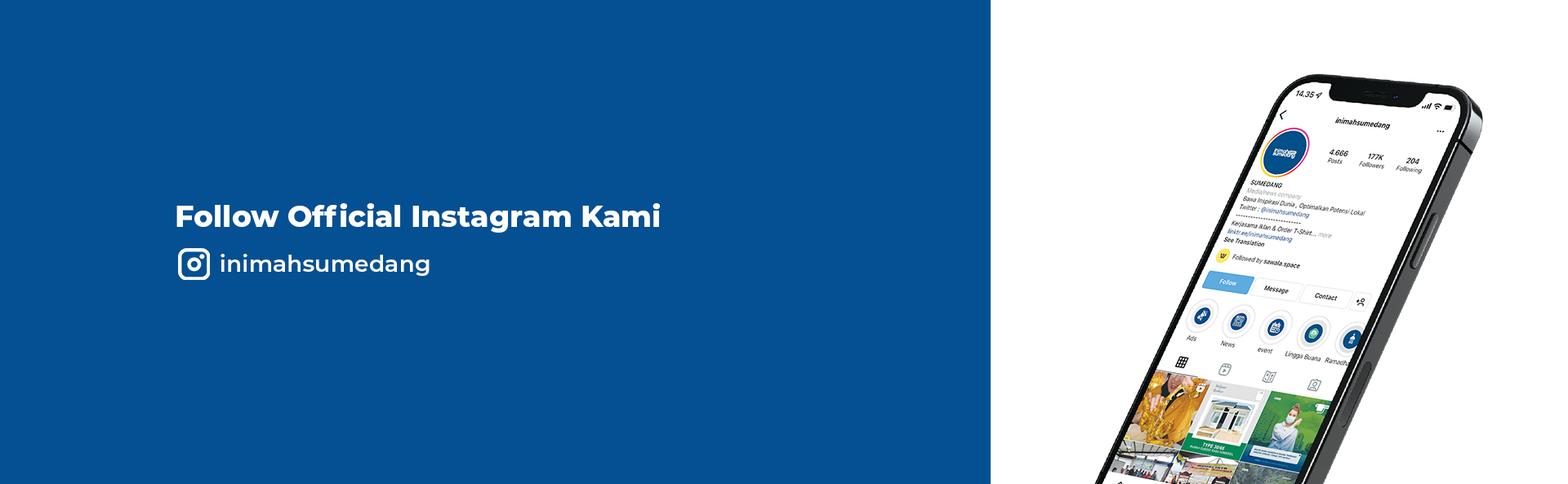

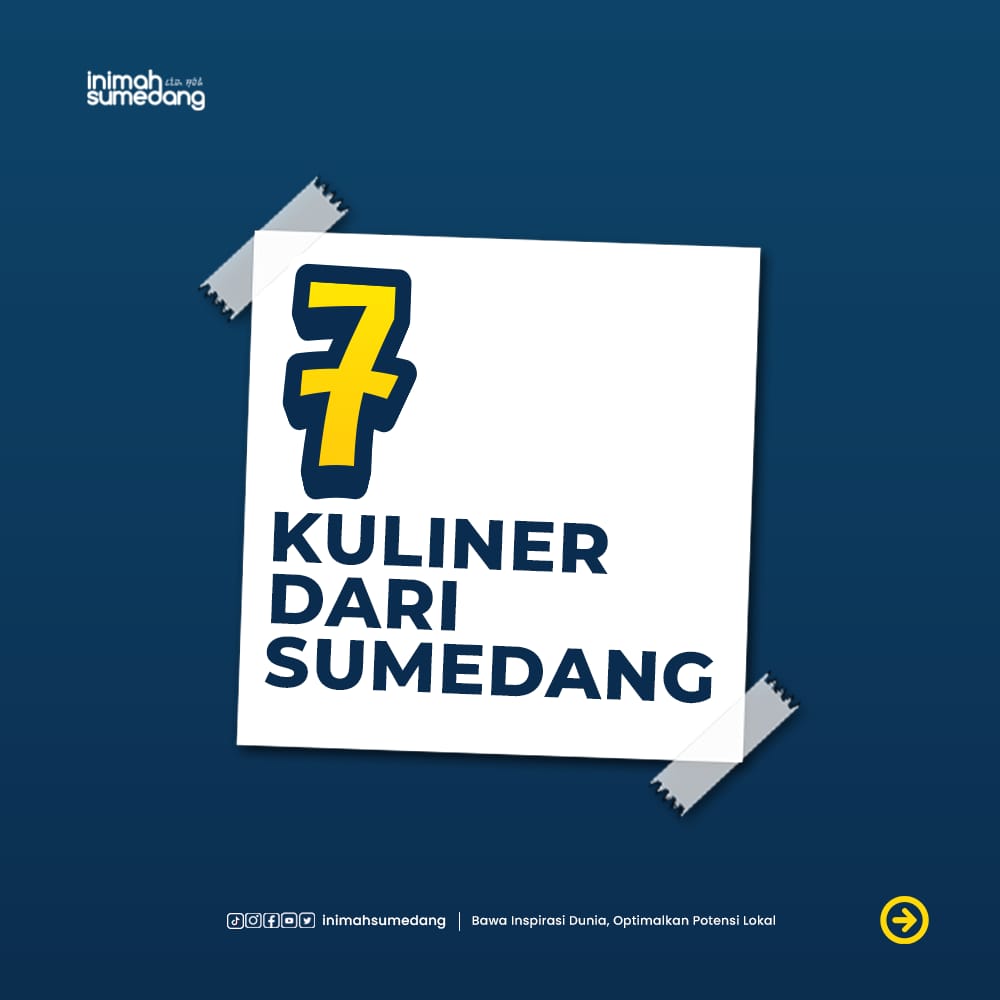
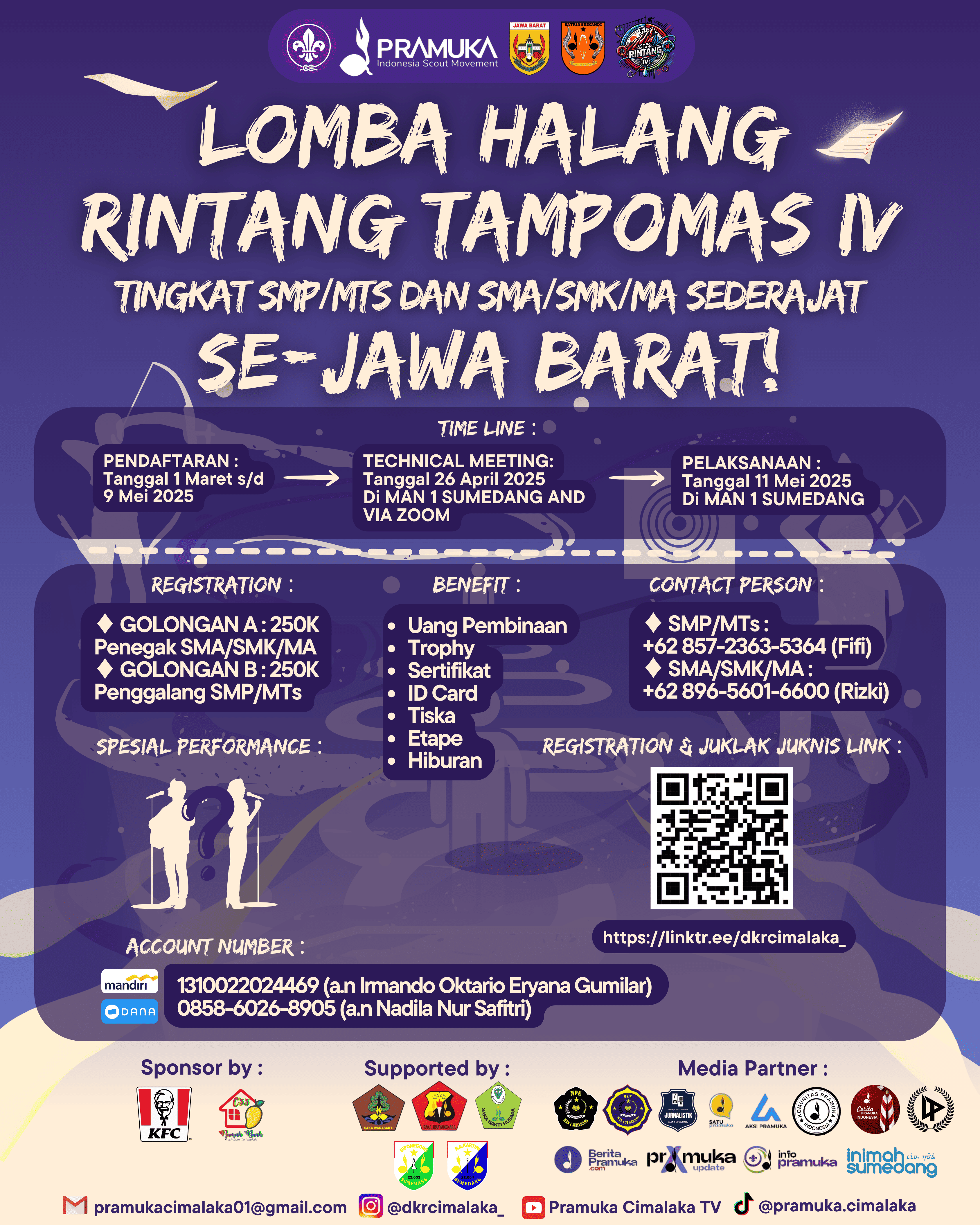


Belum ada komentar.